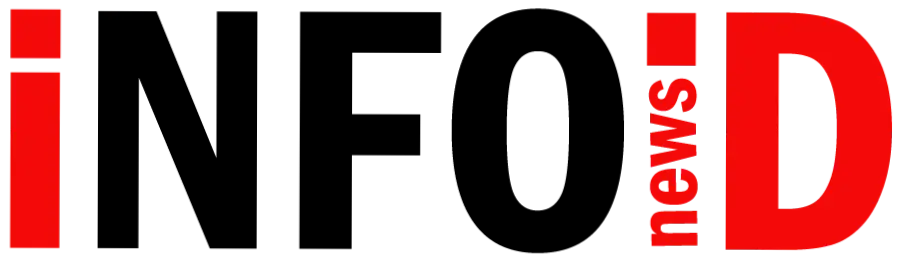*Cak Bonang Adji Handoko, Koordinator Presidium Srawungan Arek Kampung Suroboyo (AKAS)
Bencana tidak menunggu persiapan oleh apapun dan siapapun. Gempa, banjir, longsor, atau angin topan datang tiba-tiba, merobek rumah, menghancurkan fasilitas, dan menelan banyak nyawa melayang.
Ribuan orang mengungsi, trauma melanda, dan masyarakat kehilangan arah. Di saat seperti ini, media memiliki peran yang sangat menentukan: apakah menjadi penonton tragedi, atau menjadi penyelamat kemanusiaan?
Jurnalisme kebencanaan bukan sekadar menulis angka korban atau memotret reruntuhan. Ia adalah praktik yang menempatkan manusia—korban dalam peristiwa—di pusat liputan.
Setiap korban yang terdampak adalah individu dengan nama, keluarga, cerita hidup, dan trauma yang unik. Mereka bukan objek dramatis untuk klik atau pemberitaan sensasional. Menjaga martabat korban adalah tanggung jawab dan kewajiban moral jurnalis.
Lalu, apa yang diperlukan seorang jurnalis untuk menulis informasi yang humanis dan bermartabat saat bencana melanda?
*1. Empati yang Dipandu Etika.*
Jurnalis harus hadir dengan empati, tetapi tetap profesional. Tidak semua yang terlihat dramatis layak ditayangkan atau ditulis. Sebelum mewawancarai korban atau mengambil gambar, tanyakan pada sanubari kita: Apakah liputan ini memanusiakan mereka, atau justru mengeksploitasi penderitaan? Empati yang dipandu etika mencegah liputan menjadi voyeurisme duka dan menjaga kredibilitas media.
*2. Verifikasi Fakta dan Sumber Terpercaya.*
Bencana adalah lahan subur bagi disinformasi. Rumor tersebar cepat, foto lama dipasang ulang, dan hoaks bisa secepat kilat menyesatkan publik. Seorang jurnalis harus memastikan informasi berasal dari sumber resmi—BPBD, BNPB, posko relawan, atau pejabat yang dapat dipercaya. Data yang salah tidak hanya merusak reputasi media, tetapi bisa membahayakan korban dan masyarakat.
*3. Konteks dan Narasi yang Memanusiakan.*
Menulis liputan bencana bukan sekadar menceritakan apa yang terjadi, tetapi mengapa dan bagaimana. Jelaskan konteks bencana: lokasi terdampak, kondisi pengungsian, akses bantuan, dan upaya warga atau relawan untuk bertahan. Sorot kisah manusia yang berjuang, solidaritas warga sekitar, atau usaha pemulihan pasca bencana. Narasi yang memanusiakan membuat publik memahami korban sebagai manusia utuh, bukan sekadar angka statistik atau judul klik.
*4. Penggunaan Bahasa dan Visual yang Sensitif.*
Bahasa yang dipilih jurnalis harus empatik, bukan sensasional. Judul tidak boleh menakut-nakuti atau mengekploitasi trauma. Foto dan video harus menghormati privasi korban. Hindari menyorot jenazah atau luka parah secara berlebihan. Sebaliknya, fokuskan pada aksi penyelamatan, solidaritas kolèktif, atau langkah pemulihan secara tepat. Visual yang sensitif mampu menyampaikan duka tanpa merendahkan martabat manusia.
*5. Perlindungan Identitas Korban Rentan.*
Anak-anak, lansia, dan kelompok minoritas sangat rentan saat bencana. Jurnalis harus menghormati hak mereka untuk tidak tampil di media tanpa izin. Menjaga identitas korban adalah bagian dari tanggung jawab profesional—karena martabat mereka lebih penting daripada eksposur berita.
*6. Liputan Pascabencana dan Akuntabilitas.*
Bencana tidak berhenti setelah air surut atau gempa reda. Banyak korban menghadapi di tenda pengungsian lebih lama, distribusi bantuan yang tidak merata, dan trauma psikologis. Jurnalis harus menindaklanjuti liputan: memantau distribusi bantuan, menyoroti masalah struktural, dan memastikan pemerintah atau lembaga terkait yang bertanggung jawab. Liputan pascabencana adalah bentuk nyata dari jurnalisme kemanusiaan.
*7. Refleksi dan Koreksi.*
Jurnalis harus siap melakukan koreksi cepat jika ada kesalahan informasi. Kejujuran dan transparansi pemberitaan akan memperkuat kepercayaan publik, sekaligus menunjukkan bahwa peran serta media sangat serius memegang tanggung jawab kemanusiaan.
Contoh praktik jurnalisme yang bermartabat terlihat saat banjir Sumatra dan Aceh akhir 2025. Beberapa media menunggu data resmi, memetakan lokasi pengungsian, dan menyoroti jalur aman. Reporter mewawancarai korban dengan izin, menekankan kisah solidaritas dan pemulihan, bukan hanya linangan air mata. Publik mendapat informasi yang benar-benar menyelamatkan nyawa—tanpa mengeksploitasi trauma.
Bandingkan dengan beberapa portal daring yang terburu-buru mempublikasikan foto dramatis dengan judul sensasional. Hasilnya, masyarakat bingung, panik, dan salah langkah. Di sinilah perbedaan jelas antara jurnalisme kemanusiaan dan jurnalisme sensasional: yang pertama memprioritaskan manusia, yang kedua memprioritaskan algoritma klik.
Bencana alam adalah ujian moral bagi insan pers. Jika jurnalis gagal, korban kehilangan martabatnya, dan publik kehilangan akal sehatnya. Sebaliknya, liputan yang bermartabat bisa menyelamatkan nyawa, memicu solidaritas, dan memastikan keadilan tetap terjaga.
Jurnalisme kebencanaan adalah jurnalisme kemanusiaan.
Ia menjaga manusia tetap manusia, nalar publik tetap jernih, dan keadilan tetap terpantau. Jika pers hanya menonton, kita semuanya ikut tenggelam.
Sebagai jurnalis, pertanyaannya sederhana: Apakah Anda akan menulis untuk klik, atau untuk kemanusiaan?
Setiap kata, setiap foto, setiap judul adalah keputusan etis. Saat meliput bencana, jangan biarkan ambisi, tekanan waktu, atau algoritma media sosial mengalahkan tanggung jawab Anda kepada korban. Menjadi saksi tragedi bukan cukup. Jadilah suara yang memanusiakan para korban, bukan menonton dari jauh. Sekarang ayolah, jadilah jurnalis kebencanaan—yang memartabatkan korban. (*)
Editor : Tudji Martudji