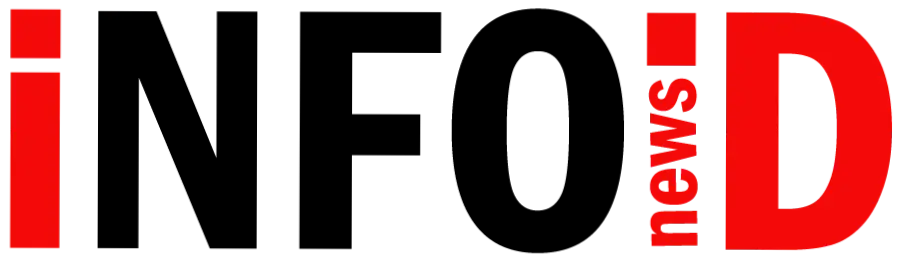SURABAYA, iNFONews.ID - Bagi sebagian orang di kota, sound horeg hanyalah dentuman bass yang memecah malam desa, ritme tanpa kata, pesta tanpa wacana.
Bagi sebagian orang di desa, ia adalah malam yang hidup. Malam yang membuat semua orang keluar dari rumah, malam ketika jalanan menjadi panggung, dan setiap orang menjadi penonton sekaligus bagian dari pertunjukan.
Dari atas, penguasa melihatnya sebagai ventilasi terkunci: katup pelepas tekanan yang aman. Dentuman ini membiarkan energi sosial meletup dengan lembut, tidak pernah memberi jalan bagi udara segar menuju ruang politik.
Dari bawah, warga melihatnya sebagai alasan untuk melupakan sejenak beratnya hidup. Tidak ada tagihan, tidak ada harga beras, tidak ada beban lain. Hanya tubuh yang ikut bergerak, meski kaki tidak menari.
Elite lokal hadir di gelaran massal, aparat desa memberi restu, warga patungan untuk mendatangkan set up raksasa dengan subwoofer yang mengguncang tubuh. Fenomena ini jarang lahir sepenuhnya dari bawah; ia adalah hibrida antara elite lokal yang menguasai panggung dan elite sound horeg yang menguasai dentuman.
Relasi itu jarang sejajar. Lebih sering subordinatif, di mana dentuman menjadi alat patron untuk membeli loyalitas dan membungkus kekuasaan dengan citra “pemimpin rakyat”.
Warga tahu itu mahal. Tapi mereka tidak menganggapnya pemborosan. Justru itu tanda bahwa mereka masih bisa mengumpulkan sesuatu bersama-sama. Ketika kepala desa atau tokoh kampung ikut berdiri di tengah kerumunan, mereka merasa ditemani. Entah itu tulus atau demi skor politik, yang penting malam itu terasa milik semua.
Pola ini klasik dalam antropologi politik: roti dan sirkus. Bedanya, di sini roti diganti bass. Sama seperti Festival Panathenaia di Athena, era Yunani Kuno. Di mana rakyat berkumpul merayakan Dewi Athena, dengan sajian atletik, tarian, hingga pemujaan. Namun algoritma sosial hari ini bisa jadi akan bergerak jauh lebih cepat dari kalkulasi patron desa di kemudian hari.
Generasi pelaku dan penikmat sound horeg hidup di dunia yang mendokumentasikan dirinya sendiri: setiap momen, setiap kelalaian, setiap ketidakadilan terekam dan tersebar dalam hitungan menit. Kesalahan patron bisa viral, mencabut legitimasi yang selama ini mereka anggap aman.
Dan warga bukan tidak sadar. Mereka mungkin jarang membicarakan politik di sela dentuman, tapi mereka tahu siapa yang hadir dan siapa yang hanya datang saat butuh suara.
Sementara di sisi yang lain, kelas menengah urban tidak menjadi jembatan yang menghubungkan dentuman ini dengan ruang publik yang lebih luas. Sebaliknya, mereka menjadi dinding yang memantulkan suara kembali ke pelakunya. Tidak ada rasa ingin memahami, tidak ada pembacaan estetika, apalagi dukungan politik. Yang ada hanya keluhan tentang kebisingan.
Namun bagi komunitas sound horeg, keluhan itu mungkin hanya mempertegas batas “kami” dan “mereka”. Dan dalam batas itu, dentuman terasa lebih murni. Tak perlu persetujuan orang luar untuk tetap hidup.
Sejarah di tempat lain memperingatkan bahwa musik tanpa pesan verbal pun bisa menjadi politik begitu ruangnya dibatasi.
Rave di Inggris berubah menjadi simbol perlawanan setelah dilarang lewat Criminal Justice and Public Order Act 1994. Cumbia villera di Argentina memperkuat identitas rakyat tertindas setelah diusir dari media mainstream. Dangdut pantura di Indonesia diambil alih televisi dan politisi menjadi mesin mobilisasi.
Komunitas sound horeg mungkin juga tahu, kalau suatu hari dentuman ini dilarang, itu akan jadi masalah. Bukan hanya karena hiburan hilang, tapi karena satu-satunya momen ketika mereka merasa setara ikut dirampas. Dan ketika itu terjadi, mungkin untuk pertama kalinya mereka akan memikirkan bagaimana bersuara lebih nyaring dan artikulatif.
Hari ini, sound horeg belum punya korpus lirik atau narasi politis. Belum ada intelektual organik yang meramunya menjadi kesadaran kolektif. Tetapi kekosongan ini bukan jaminan dentumannya akan jinak selamanya.
Sejarah subkultur menunjukkan, komunitas yang hari ini tunduk bisa menjadi arus liar ketika ada figur artikulatif, insiden pemicu, dan ruang distribusi yang tepat.
Di jalanan, mereka mungkin tidak mengucapkan kata “perlawanan”. Tapi dalam diam, mereka tahu: air yang terlalu lama ditahan bisa membuat bendungan jebol.
Jika kekuasaan adalah medan yang cair, relasi antara elite lokal dan sound horeg bisa berubah kapan saja. Ada patron yang tahu menjaga jarak aman, memberi ruang berekspresi tanpa membiarkan dentuman menjadi genderang.
Ada monster yang terlalu rakus, menguras legitimasi tanpa memberi perlindungan, dan pada akhirnya memicu komunitas mencari jalan sendiri. Ada pula ledakan emosional yang lahir dari satu peristiwa represif, yang menyatukan komunitas tanpa rencana ideologis, tapi dengan kekuatan solidaritas spontan. Dan ada kemungkinan yang lebih berbahaya bagi penguasa: lahirnya intelektual organik dari dalam komunitas sendiri yang tahu bagaimana mengubah dentuman menjadi bahasa politik. Ini adalah simulasi sosial, ketika tekanan dari dalam terlalu besar dan katupnya sudah macet atau keropos.
Hari ini, dentuman itu masih menyerupa pesta. Tapi katup yang terlalu sering digunakan tanpa perawatan akan macet. Dan katup yang macet tidak sekadar berhenti berfungsi, ia meledak. Penguasa yang gagal membaca algoritma sosial, yang mengira dentuman ini hanya miliknya untuk diatur, ia bisa berubah menjadi monster penghisap darah dan mati oleh jeritan sistem yang pernah ia pelihara.
James C. Scott dalam Weapons of the Weak mengingatkan kita, perlawanan sering lahir bukan dari manifesto megah, tapi dari akumulasi kecil yang dianggap sepele. Dalam dunia sound horeg, dentuman itu bisa tetap menjadi pesta… atau tanpa sadar, berubah menjadi genderang.(*)
Eddy Prastyo | Editor in Chief | Suara Surabaya Media
“Dentuman-nya Rakyat, Remote-nya Penguasa”
Editor : Tudji Martudji